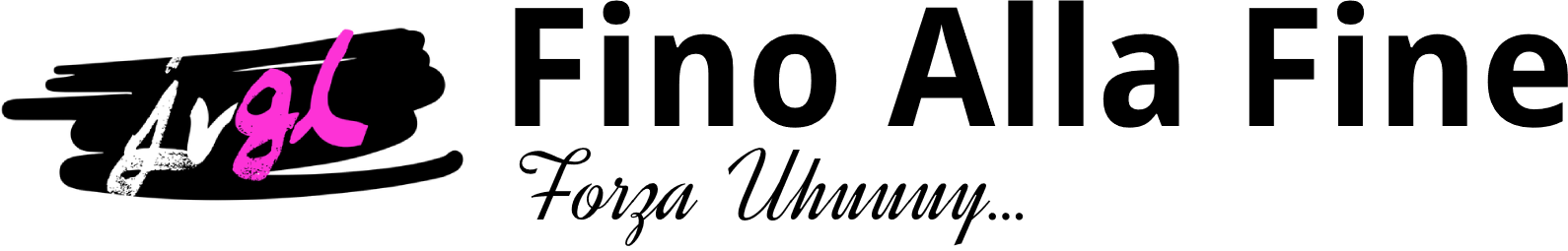Rivalitas Fans Tidak Harus Seperti Ini, Kawan

Sewaktu kecil, saya sering menonton kejuaran gulat hiburan WWE Smackdown di televisi. Kenapa disebut kejuaraan? Karena memang ada gelar yang diperebutkan di sana. Dan kenapa disebut hiburan? Ya karena para pegulat yang bertanding, tidak benar-benar berkelahi sebagaimana terlihat.
Semua yang disuguhkan di gelaran Smackdown, sudah terlebih dulu ditentukan jalan ceritanya. Para pegulat, rutin berlatih koreografi gulat di atas ring, sehingga mereka tahu ke bagian tubuh mana mereka harus memukul, bagaimana teknik membanting, mencekik, bahkan melakukan lompatan.
Tak jarang untuk memainkan emosi penonton, para pegulat melakukan dramatisasi terlebih dulu sebelum bertanding. Mereka saling me-roasting satu sama lain, adu mulut, baru kemudian pukul-pukulan.
Jagoan saya dulu, The Rock. Si ganteng yang sarkastik, lincah, gesit, tapi sering dikerjai dua musuh bebuyutannya, Stone Cold & Triple H. Dua-duanya sama-sama menyebalkan. Stone Cold selalu menjadi tokoh yang sukar ditebak. Kadang, muncul cuma untuk melakukan hal-hal narsis, minum bir di atas ring, atau duduk di kursi komentator.
Triple H juga sebelas-dua belas. Dia licik, culas, sering menginterupsi pertandingan dengan kecurangan bersama gengnya, D Generation X. Benci sekali saya melihatnya.
Bukan sekali-dua kali, keduanya menjadi seteru bagi idola saya, The Rock. Meski kadang tak dipertemukan dalam sebuah pertandingan, baik Stone Cold, apalagi Triple H, selalu saja muncul ke tengah-tengah pertandingan The Rock, kemudian mengganggunya, dan akhirnya, The Rock menderita kekalahan.
Butuh belasan tahun bagi saya memahami, bahwa yang dipertontonkan saat itu, tak lebih dari sekadar pertunjukan seni beladiri. Tak ada yang benar-benar “terluka” di sana.
Memang, sih. Ada banyak sekali pegulat yang patah tulang, kepalanya bocor, bahkan sampai koma. Tapi tak ada satupun dari itu semua yang lahir dari kesengajaan. Semua diatur secara rinci, profesional, hingga minim terjadi kecelakaan.
Semenjak saya tahu, bahwa suguhan dalam pertandingan Smackdown adalah tidak murni “bertarung”, maka saya jadi lebih enjoy menikmati acara ini. Itulah pentingnya, mencari tahu how the world works, pada aspek apapun. Termasuk olahraga.
Saya jadi makin senang saat ada gimmick-gimmick perseteruan di luar arena, semisal, bangkit dari kubur ala The Undertaker, kisah cinta Triple H & Stephanie, atau intrik-intrik jahat dari sang empunya hajat, Vince Mc Mahon.
Saya jadi berpikir, konsep menikmati hiburan dalam sebuah olahraga, seharusnya juga bisa dibawa ke ranah lain, ke sepakbola salah satunya.
Sebagaimana saya mengidolai The Rock, seringkali saya dibuat kesal ketika ia kalah. Namun di sanalah letak hiburannya. Ada emosi dan ekspektasi yang dipermainkan.
Ekspektasi melihat sang jagoan meraih kemenangan, harus pupus karena dicurangi, diperlakukan tak adil, menjadi bagian yang lumrah. Ini adalah suatu suguhan menghibur dari Smackdown.
Tak mungkin selamanya jagoan yang saya dukung, bisa terus-terusan menang. Sebab tentu bagi orang lain, bisa jadi The Rock bukanlah jagoannya. Ada banyak orang yang justru percaya Stone Cold atau bahkan Triple H, adalah jagoannya. Dan ini biasa terjadi.
Saat The Rock menang, saya bisa menikmati euforianya. Sebaliknya saat kalah, saya bisa menikmati bagaimana di pekan berikutnya, The Rock berupaya bangkit dan membalas lawan-lawannya.
Sahabat saya, Wahyu Hidayaturo, begitu terobsesi pada John Cena. Tetapi saat The Rock dan Cena berhadapan, kami berdua tak sampai ledek-ledekan, apalagi menghujat. Kami benar-benar larut menikmati pertandingan keduanya. Menyenangkan.
Tak penting lagi siapa yang kalah, siapa yang menang. Menyaksikan keduanya bertanding gagah berani saja, sudah menjadi kepuasan tersendiri. Lantas apa lagi yang mau dicari?
Kompetisi memang seni mempermainkan ekspektasi. Begitupun di epakbola. Sayangnya banyak orang menyerah untuk berpikir jernih, mereka rela kehilangan kewarasan oleh ekspektasinya sendiri.
Ada banyak yang menggilai klub tertentu, berangan-angan klub yang digilainya, menyapu bersih semua gelar juara, namun tak cukup realistis melihat kondisi klub yang didukungnya itu.
Baru solid secara materi pemain saja, sudah sesumbar sana-sini. Baru konsisten di beberapa pertandingan, sudah congkak bak Fir Aun. Padahal masih banyak PR yang tak terlihat. Ya, seperti kata pepatah. Semut di seberang lautan terlihat. Gajah di depan mata, gaib. Ini berlaku umum, sih.
Maka jangan kaget, ketika timnya terpeleset, yang pertama kali terlintas di benak orang-orang ini, sudah bukan lagi hal-hal teknis, melainkan klenik, cocoklogi, sampai yang lebih absurd lagi, ya teori konspirasi!
Misal, saat klub Galernitana kalah, para Galernisti bukannya melihat apa yang perlu dibenahi di dalam klubnya, malah justru menyalahkan hal-hal di luar itu.
Menyalahkan varietas rumput stadion, hitung-hitungan feng shui, salah Jokowi, salah Anies, dsb. Padahal persoalannya, tak berhulu di sana.
Saya pun tak heran, ketika misal, Persijembut Jember Utara memuncaki klasemen Liga Primer Jametnesia. Para fans Jembutnisti mendadak bereuforia lebay di sana-sini. Tidak semua, sih. Banyak yang menyikapinya woles. Tapi ya, kalah berisik dari yang sedikit ini.
Saya sih, maklum. Kan selama ini klub kesayangan mereka berkutat di papan tengah. Maka ketika sekarang Persijembut ada di pucuk, ekspektasi sekian tahun mereka akhirnya terpenuhi juga.
Ironisnya adalah, masih banyak orang yang belum cukup merasa puas, meski ekspektasinya sudah terpuaskan. Saya ulangi, banyak orang yang belum cukup merasa puas, meski ekspektasinya sudah terpuaskan.
Sudah ada di puncak, tapi egonya masih lapar, masih haus pengakuan & nafsu ingin pamer. Padahal balik lagi, ini cuma kompetisi, tak lebih dari sebuah seni mempermainkan ekspektasi. Itu saja.
Lucu, walau sebenarnya tak lucu, karena untuk memahami konsep dasar ini saja, orang-orang semacam ini menolak paham. Kasihan. Tapi lumayan sih, buat nambah-nambah hiburan. Lumayan bersyukur rasanya, tiap melihat kelakuan spesies-spesies gagal evolusi ini.
Memang, akan selalu ada orang-orang macam @akmalmilan01 atau @milantitooo, berdiri di sisi manapun. Bahkan di dalam tubuh Juventini sekalipun.
Padahal tak ada hubungannya foto selfie Alexa Saffira dengan rivalitas Juve dan Inter Milan. Pun dengan pose-pose gemesin Aurellia Donna, dengan tensi Juve dan AC Milan. Keduanya sama-sama menyenangkan dilihat, cuma rasa iri saja yang membuat keduanya jadi sasaran hatespeech. Menyedihkan, memang.
Apa sih susahnya nonton bola dengan woles? Kalau saya dan Wahyu Hidayaturo bisa santai nonton Smackdown, walau berbeda jagoan. Mengapa kita sulit melakukan hal yang sama di sepakbola?
Ya emang kenapa kalau kita saling berbeda dukungan, wahai, Milanisti mazhab Imam Akmal Tito? Di mana korelasinya memakai masa lalu Pesotto, sebagai bahan mematahkan opini Asi Asmaria? Sakit! Rivalitas tak seanying itu, Ki Sanak!

Terus terang saya sampai tak kuat membayangkan, jika orang-orang ini, Akmal dan Tito, juga menggemari olahraga yang bersifat hiburan macam Smackdown. Barangkali seumur hidup, mereka akan percaya mentah-mentah; baik The Rock, Stone Cold, maupun Triple H, ketiganya memang benar-benar saling bermusuhan?
Atau bahkan jika pola pikir mereka dipakai menyikapi persoalan yang lebih serius, semisal membedah kontsalasi politik, mengupas kontestasinya, atau yang lebih fundamental sekalian, memperbincangkan teologi?
Gimana mau dapet tiket ke Jannah, kalau Iqra saja tidak mau…
Entahlah… Jujur, saya tak punya dendam pribadi terhadap siapapun. Tidak pada Akmal, pun pada makhluk yang avatarnya lebih cakep dari wajah aslinya, Tito. Di luar sana, akan selalu ada orang-orang macam ini, bahkan berdiri di sisi yang sama dengan kita. Hanya beda versi, dan beda jersey saja.
Setidaknya lewat tulisan ini, saya memiliki pengingat bagi diri sendiri, supaya esok lusa, saya tak berubah menjadi seanying itu.
Salam, rambut ijo!